Beberapa waktu lalu, saat saya dan teman-teman membicarakan aksi penolakan pengesahan RUU TNI, tiba-tiba ada seorang kawan menyeletuk, “Kenapa sih, kalo ada isu genting kayak gini selalu ditutupin sama kasus selingkuh?”
Saya pun termenung dan mengingat kembali bahwa kasus ini tak terjadi sekali. Timbul pola-pola yang telah kita semua ketahui. Kasus yang menyeret nama ‘baik’ negara hingga hampir menimbulkan lubang menganga, ditutupi oleh skandal panas yang selalu membawa tubuh dan seksualitas perempuan sebagai tamengnya.
Kali ini, saat ramai pembicaraan kritis terkait penolakan RUU TNI, nama Lisa Mariana ramai menghiasi linimasa media sosial dan portal berita daring. Melalui akun Instagramnya, Lisa mempublikasikan klaim bahwa ia memiliki hubungan personal dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, hingga akhirnya melahirkan seorang anak perempuan.
Sejak unggahan itu, publik bereaksi keras. Seksualitasnya dieksploitasi, tubuhnya dikomentari, dan kehidupannya dijadikan tontonan massal. Namun yang patut dipertanyakan bukan tentang kebenaran klaim Lisa, melainkan mengapa skandal seperti ini kerap digunakan, dan siapa yang paling diuntungkan?
Tubuh Perempuan sebagai Arena Politik
Dalam Caliban and the Witch (2021), Silvia Federici mengungkap bahwa tubuh perempuan dalam kapitalisme bukanlah entitas netral atau semata-mata biologis. Ia adalah pabrik sosial—tempat berlangsungnya kerja reproduktif, seperti melahirkan, merawat, menyusui, dan menjaga kehidupan—yang dikontrol secara ketat oleh negara, institusi agama, serta norma-norma sosial demi kelangsungan sistem ekonomi-politik yang dominan.
Kasus Lisa Mariana mencerminkan semua itu secara telanjang. Dalam konferensi persnya, Lisa tak hanya berbicara sebagai individu yang mengalami relasi personal, tapi dipaksa untuk membuka seksualitasnya ke ruang publik. Ia menjelaskan secara detail kapan terakhir kali berhubungan intim, menyatakan dirinya tak pernah bersama laki-laki lain, hingga harus meyakinkan publik soal identitas biologis anak yang dikandungnya. Semua itu diungkap bukan karena ingin, tapi karena ia harus membela diri, menjelaskan, dan membuktikan bahwa tubuhnya layak didengar.
Di sinilah kekerasan simbolik itu bekerja; ketika perempuan tak hanya dikontrol secara fisik, tapi juga secara naratif. Lisa harus mengungkapkan hal yang sangat privat demi mempertahankan posisinya sebagai “perempuan yang punya kredibilitas”. Tubuhnya menjadi arena penjelasan, pembelaan, dan penghakiman. Sementara, laki-laki yang dituduh tak perlu menjelaskan ranjangnya kepada siapa pun.
Federici menyebut bahwa kekuasaan terhadap tubuh perempuan bekerja tidak hanya dalam bentuk larangan atau perintah, tapi juga lewat disiplin naratif, yakni dorongan untuk berbicara sesuai logika kekuasaan. Sehingga, tubuh perempuan hanya dianggap sah jika tunduk pada pembenaran eksternal; perempuan “baik-baik”. Dan jika tak memenuhi kategori itu, tubuhnya akan diposisikan sebagai sesuatu yang liar, salah, atau pantas dihukum.
Respons publik pun menunjukkan hal serupa. Setelah Lisa mengungkapkan hal tersebut, gelombang hujatan berdatangan. Tubuhnya dikomentari, fotonya dibandingkan, dan moralitasnya diragukan. Bahkan ketika sebagian netizen sadar bahwa kasus ini bisa jadi pengalihan isu terhadap pengesahan RUU TNI, cacian terhadap Lisa tak juga surut.
Skandal sebagai Alat Pengalihan
Dalam The Routledge Companion to Media and Scandal (2019), para peneliti menyatakan bahwa skandal tak muncul secara alami, melainkan dikonstruksi oleh media melalui proses framing yang selektif. Salah satu bagian dari buku ini “Media Framing of Political Scandals” dan Siracuse (2024), menunjukkan bahwa skandal seksual sering dibingkai secara personal yang menyoroti individu, bukan sistem.
Sehingga, hal inilah yang diharapkan oleh negara dan elit politik; menyebabkan diskusi publik bergeser dari penolakan pengesahan RUU TNI ke urusan moralitas pribadi. Mereka menganggap skandal menjadi “panggung pengalih” yang efektif karena ia menyedot emosi, memicu moral panic, dan menggeser energi publik dari wacana politik–yang masih lekat dengan maskulinitas–ke wilayah gosip dan penghakiman moral–yang dianggap lebih dekat dengan masyarakat.
Sementara itu, pada bagian “The Shifting Boundaries of Elite and Tabloid Media in Political Sex Scandals” dijelaskan bahwa skandal seksual secara konsisten memperkuat narasi patriarki. Perempuan yang terlibat dalam skandal hampir selalu digambarkan sebagai penggoda, oportunis, atau bahkan simbol dekadensi moral masyarakat.
Pada kasus Lisa, narasi ini diperkuat ketika Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara. Ia mengakui bahwa dirinya memang pernah bertemu dengan Lisa, namun terkait bantuan kuliah. Pernyataan ini bisa dibaca publik sebagai penggambaran sosok Lisa yang oportunis. Tampak jelas bagaimana relasi kuasa bekerja dalam pengelolaan narasi publik. Karena, pernyataan pihak yang memiliki otoritas sosial dan jabatan sering kali secara otomatis dianggap lebih kredibel.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Di media sosial, terutama X, pencarian dengan kata kunci “Lisa Mariana” kini didominasi oleh akun-akun bodong yang menyebarkan video syur, foto-foto perempuan berpakaian minim, dan potongan-potongan visual yang dikaitkan dengan Lisa—entah benar atau tidak. Lagi-lagi, tubuh Lisa kembali menjadi objek kekerasan digital.
Fenomena ini menunjukkan bahwa skandal tak hanya hidup di media mainstream, tetapi juga dipelihara oleh ekosistem digital. Media sosial tidak hanya melanjutkan peran media konvensional dalam membingkai skandal, tetapi juga memperburuknya dengan membiarkan tubuh perempuan dijadikan bahan pornografi, dagangan klik, topik cuitan buzzer, dan hiburan brutal tanpa empati.
Semua ini adalah bentuk lanjutan dari kontrol dan disiplin terhadap tubuh perempuan seperti yang digambarkan Federici. Ketika tubuh perempuan tak bisa lagi dikekang secara fisik, maka ia dikendalikan melalui rasa malu, eksposur publik, dan teror digital. Perempuan yang berbicara tentang seksualitas dan reproduksi, seperti Lisa, tak hanya harus menghadapi keraguan, tapi juga serangan bertubi-tubi terhadap integritas tubuh dan identitasnya.
Disiplin Tubuh, Disiplin Sosial
Lisa Mariana tak hanya dikriminalisasi karena dugaan hubungan personalnya dengan seorang tokoh publik, tetapi juga karena tubuhnya. Setelah menggelar konferensi pers dan muncul ke publik, tubuhnya langsung menjadi sasaran komentar, seperti “beda banget sama di foto”, “aslinya ndut”, hingga “gak sesuai ekspektasi”.
Ini adalah bentuk nyata dari disciplining the female body; sebuah proses panjang yang telah dijelaskan Federici sebagai warisan patriarkal dari era perburuan penyihir di Eropa. Dulu, perempuan yang dianggap menyimpang, terlalu mandiri, atau melawan tatanan sosial akan dihukum secara fisik, seperti dibakar hidup-hidup, dipenjara, atau diasingkan.
Hari ini, tubuh perempuan yang “tidak sesuai harapan” pun juga harus dihukum melalui teknologi digital. Seperti, dicemooh di kolom komentar, dijadikan bahan lelucon, atau di-cancel oleh publik yang merasa berhak atas tubuhnya.
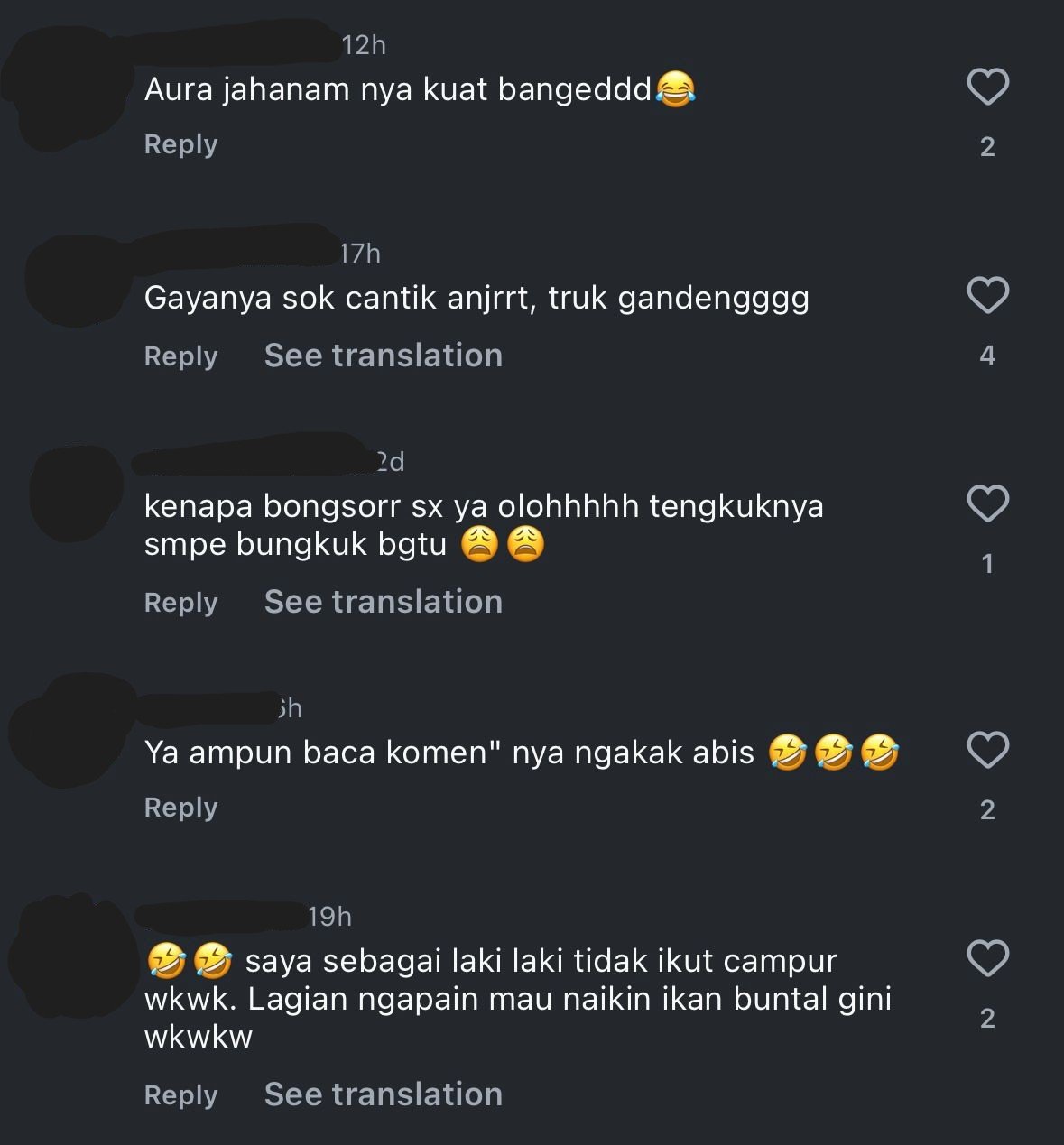
Bagian “Shame and Scandal: Making the Personal Political” memperkuat argumen ini. Dijelaskan bahwa skandal bukan hanya soal pelanggaran moral, tetapi juga mekanisme untuk memproduksi rasa malu sebagai alat kontrol sosial. Tubuh perempuan dijadikan medium politisasi, bahkan dimasukkan ke dalam arus debat publik; bukan untuk didengarkan, tetapi untuk diatur, dinilai, dan dimanfaatkan.
Lantas, Siapa yang Diuntungkan?
Sejak diciptakan, media memang tidak netral. Puglisi dan Snyder (2008) menyatakan bahwa media memilih skandal secara selektif, tergantung pada kepentingan politik yang diuntungkan. Cerita-cerita sensasional, yang bisa menenggelamkan isu serius dan sekaligus mendatangkan klik, traffic, dan atensi, akan selalu diprioritaskan. Inilah yang menjelaskan mengapa media ramai-ramai memberitakan Lisa Mariana secara masif, namun justru minim mengulas RUU TNI secara kritis.
Dan tentu saja, yang paling diuntungkan dari semua ini: negara. Ketika ruang publik sibuk membahas tubuh, seksualitas, dan moralitas seorang perempuan, negara bisa lenggang menyelipkan agenda-agenda kontroversial tanpa perlawanan berarti. Skandal seperti ini berfungsi sebagai distraksi kolektif yang mengalihkan amarah dan pengawasan masyarakat dari struktur kekuasaan ke drama personal.
Semakin viral tubuh perempuan di media, semakin senyap kerja-kerja otoritarianisme di balik layar.
Kasus Lisa Mariana bukan sekadar cerita pribadi. Ia adalah bukti bahwa tubuh perempuan masih menjadi alat kuasa yang dipakai untuk menegakkan moral, menyembunyikan krisis, dan menenangkan publik. Pada akhirnya, tubuh perempuan tak pernah bebas; ia selalu dalam pengawasan oleh negara, dan selalu dalam penghakiman oleh masyarakat.



0 comments